Huh!
Padahal peristiwa sudah terlampau lama, entah mengapa warga desa itu – tak
kunjung menerima eksekusi Entis. Mereka selalu beranggapan Entis polos. Senaif
tampangnya yang bagi sejumput orang, culun. Entis tak bersalah, Entis tak
bersalah. Begitulah selalu mereka dengung-dengungkan tiap hari. Sampai senewen
aku mendengarnya.
Aku… akulah salah satu dari sekian
regu penembak. Hingga kini, aku masih saja dirundung penasaran mengapa mereka
bisa tahu fakta aku termasuk orang ke sekian yang jadi eksekutornya.
Temanku,.salah satu anggota regu petembaknya juga berkata, “Ada salah satu sipir yang membocorkannya.
Dengar-dengar, si sipir itu menaruh respek pada Entis.”
Entis, Entis. Dirimu membuatku
termangu-mangu. Mengapakah warga masih tak bisa menerima dirimu itu salah satu
pelaku pengeroyokan sepuluh tahun silam? Bukti sudah cukup lengkap.
Saksi-saksinya juga sudah banyak mengatakan dirimu bersalah. Terkadang aku
merasa mereka semua terkecoh dengan wujudmu yang polos. Kukira, kamu itu setan bersayap malaikat.
Yah itulah kamu. Bagaimana tidak.
Bukti sudah lengkap, kamu masih saja mengelak. Oh tidak. Mengelak masih lebih
baik. Dengan mengelak, bisa saja pelaku memang tak bersalah. Tapi kamu tidak,
Entis. Komplet sudah bukti yang amat memberatkanmu, tutur katamu malah selalu
tak kunjung dipahami tim penyelidiknya. Mereka sampai mengiramu mengidap suatu
penyakit kejiwaan kronis. Namun bagiku, bukankah tiap pelaku kriminal memang
pengidap gangguan kejiwaan kronis? Andai jiwanya tak terganggu, mereka tak akan
melakukan hal-hal keji yang sulit dinalar: pembunuhan, pemerkosaan, mutilasi.
Entis, Entis. Sungguh dirimu
membuatku tak bisa merasakan tenangnya berjalan-jalan di desa ini untuk
menikmati matahari tenggelam di cakrawala barat. Sebelum kau dieksekusi,
kupingku belum panas. Tapi sekarang berbeda. Kemana pun melangkah, banyak mata
memandang sinis, banyak suara memproduksi cibiran-cibiran yang menusuk sukma.
Padahal sudah berjuta kukatakan, aku hanya menjalankan kewajiban.
Begini-begini, aku regu petembak profesional. Belum lagi, aku sudah meminta
maaf sebelum-sesudah eksekusi.
Sepertinya itu semua tak berlaku.
Mereka benar-benar menganggap Entis itu makhluk polos. Insan lugu, yang menurut
mereka tak akan mungkin melakukan pengeroyokan – apalagi hingga menyayat leher
korban. Sekali lagi, aku duduk di sebuah musala. Di bawah bokong, ada sajadah
yang menyejukan jiwa dan raga. Kudendangkan ayat-ayat suci sekedar meminta
hidayah dan pertolongan Sang Khalik. Ya Rabb, bebaskanlah hamba-Mu ini dari
kesukaran.
Bersamaan dengan kalimat terakhir
itu, seorang ustad menghampiri. Ustad itu mengenakan baju koko berwarna
magenta. Ia memandangiku tersenyum seraya berkata, “Kamu masih terganggu dengan
Entis?”
Kuhentikan rapalan ayat-ayat suci.
Aku tengok dan menjawab, “Iya, Ustad.”
Namanya Yusuf – setampan Nabi Yusuf
Alaisalam – dan ia berujar lagi, “Tak usah masduk
begitu. Santai saja.”
Aku protes. “Bagaimana tak masduk, Ustad? Segala pergunjingan
mereka membuat hidupku tak tenang. Jalan sedikit, ada mata nyalang. Pergi
kemanapun, suara-suara bernada minor memukul gendang telinga.”
Sang ustad nyengir. “Entis, Entis. Hidup-mati, kamu selalu saja bikin susah.”
Aku melongo. Rasa penasaran
menggelitik tiap kerja syarafku. Siapa sangka tokoh keagamaan di kampung ini
pro denganku.
“Ustad kenal dengan Entis?” tanyaku
mengernyitkan jidat.
“Jelas.” jawab Ustad Yusuf mantap.
“Entis itu semasa kecil badung. Suka bolos dan mengganggu rekan sebayanya.
Semasa remaja, ia pernah ketahuan merokok ataupun tawuran di lingkungan pesantren.
Namun karena dirisaukan akan merusak nama baik kampung dan ayahnya, pengelola
pesantren tak jadi mengeluarkannya. Tak heran aku, ia bisa menjadi pelaku
kriminal.”
“Hanya saja, warga selalu
menganak-emaskannya. Pemuda itu sungguh berwajah dua. Mereka tak tahu saja,
orang yang mereka dukung itu punya dua kepribadian. Satu sisi, berkepribadian
layaknya domba; sisi lain menjelma jadi serigala.”
“Terus mengapa Ustad tak membantu
kami menetralisir masalahnya?” selaku.
“Buat apa?” ujar Ustad Yusuf. “Pengelola
pesantren, masjid, dan musala terus memberitahukan kebenarannya. Hanya saja
warga selalu keras hatinya. Mereka tak percaya. Entis itu benar-benar sukses
menciptakan citra positif – atau mungkin saja ia menyuapnya. Ah, tapi dosa,
bukan, ber-suudzon itu?”
“Tapi warga perlu tahu,” potongku
lagi. “walau kebenaran itu menyakitkan.”
“Sudahlah, ikhlaskan saja,” Ustad
Yusuf memukul pundakku. “Bukankah seseorang yang tak membuka aib orang lain,
kelak Allah akan menutup pula aib orang itu di hari kiamat. Lagipula pembalasan
itu murni hak Allah. Tak baik kita melangkahinya.”
Ustad Yusuf ada benarnya juga.
Pembalasan itu hak-Nya. Soal bagaimanakah amal ibadah Entis itu urusan dia dan
Allah. Tak bagus pula, kita berusaha mengambil hak absolut-Nya. Walaupun begitu,
aku sudah melangkahi-Nya. Aku dan kawan-kawan regu petembak mengambil hak-Nya
untuk memanggil pulang salah satu umat-Nya. Tapi itu juga kulakukan karena
negeriku ini masih pro-hukuman mati. Mumet.
Pertemuanku dengan Ustad Yusuf
benar-benar mencerahkan. Ia laksana malaikat. Kedatangannya membawa mukjizat.
Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, mata dan bibir mereka jadi berubah
simpati padaku. Akhirnya telinga dan mataku dapat beristirahat dari
perihal-perihal negatif. Sungguh petang yang menyenangkan. Tukang ojek yang mencibiriku berubah perhatian.
Mereka malah tersenyum. Ganjil.
“Eh, Pak Andi, mau pulang?” tawar
salah satu dari mereka menawariku motor tambangnya itu. “Mau saya antar, Pak?”
Aku tersenyum kecut.
Sepertinya ia berbakat meramal. Tapi
ia bukan peramal. Awam pun akan bertanya, “Pak Andi masih marah?” jika melihat
ke belakang – apalagi di belakang penuh borok.
Tak kujawab. Anehnya, aku malah naik
motor bebek bututnya itu. Dengan girangnya, karena bisa menebus kesalahan, ia
menyetarter motor bututnya itu. Mungkin dari spionnya, ia bisa tahu aku mangkel.
“Pak Andi, saya mewakili warga
sekampung minta maaf yah. Saya juga baru tahu bagaimana jeleknya Entis itu.
Selama ini, ia selalu bersikap manis tanpa diketahui busuknya hatinya. Semuanya
tertipu oleh topeng yang ia kenakan.” Ia membuka keheningan yang sudah cukup
lama berlangsung setelah meninggalkan pangkalan.
“Oh begitu.” timpalku. “Ada angin apakah kalian
semua bisa insyaf?”
“Barusan keluarganya Entis
meninggalkan kampung. Sebelum pergi, mereka meminta maaf hampir ke seluruh
warga. Di sela-sela itulah, ayahnya bilang Entis memang layak dieksekusi. Dua
hari lalu, mereka memberesi kamar Entis dan tahulah mereka apa yang terjadi
sebenarnya. Di lemarinya, penuh senjata-senjata dan juga botol-botol minuman
keras. Bahkan ada pula, selinting ganja.”
Kala
ia menceritakan itu semua, suara deruman motornya bagaikan tak terdengar.
Seolah-olah suara-suara di sekitar kami berdua terisap – entah karena apa.
Suara si tukang ojek jadi terdengar begitu nyaring. Nyaring
senyaring-nyaringnya.
Tak ada niat aku untuk membalas
ucapannya. Niatku… hanyalah memandangi langit-langit malam. Malam ini,
langitnya berwarna pekat sekali. Sebetulnya tak terlalu pekat. Sebab ada
beberapa bintang tampak, juga sinar rembulan begitu terangnya. Terhadap purnama
itulah, aku menengadah ke atas dan berucap syukur pada Tuhan dalam sanubari.
Yah Rabb, terimakasih atas campur tanganmu.
*****
Arkian, sepuluh tahun sudah
terlewati. Sudah lama kutinggalkan profesiku sebagai regu eksekutor. Aku sadar,
profesi yang kujalani waktu itu hanya menambah panjang daftar dosaku. Sudah aku
melangkahi Sang Khalik, belum lagi ditambah dengan dosa-dosaku yang lainnya.
Kini aku menekuni profesi lainnya. Jadi dosen.
Aku juga sudah tak berada di daerah
itu lagi. Aku tinggal bermil-mil jauhnya dari daerah itu. Walaupun demikian,
Entis tetap ada di memoriku. Ia tak hanya azal, tapi juga sungguh kekal
selamanya. Walau sempat dibuat kelimpungan, ia mengajariku suatu hal: jangan
membeli satu makanan hanya karena bungkusnya menarik hati.
Pelajaran itu masih tertanam di ulu
hatiku. Tertancap begitu kokohnya. Saking mengempat kokohnya, itu membuatku tak
langsung cepatnya menarik kesimpulan dalam berhadapan dengan kasus-kasus
homogen. Selalu berpikir dua kali dan membuatku tampak lambat memutuskan oleh
rekan-rekanku di sekretariat. Tapi bukankah ada pepatah yang mengatakan, “Biar
lambat, asal selamat.”?
Seperti saat ini. Aku dan
rekan-rekan dosen dihadapi oleh suatu kasus. Kasus ini sama seperti kasus
Entis. Hanya berbeda sedikit. Bukan kasus pengeroyokan, namun kasus plagiat.
Pelakunya tak kunjung mengakui perbuatannya. Ia terus berbicara berputar-putar
seperti sebuah komedi putar. Bikin pusing saja. Apakah ini selalu menjadi
pembawaan manusia yang tak pernah mau mengakui kesalahannya? Padahal nyatanya
ia sudah terbukti bersalah.
Pelakunya juga menyerupai Entis.
Beberapa dosen tak percaya ia melakukan plagiasi hanya untuk lulus semata.
Semasa kuliah, ia bukan langganan kasus. Tak pernah absen kuliah maupun kena
cekal karena masalah absensi. Teman-teman mahasiswanya juga beranggapan sama.
Tapi bukti sudah lengkap. Skripsinya sudah terbukti mengandung unsur plagiat.
Ancamannya… kalau tak batal kelulusannya, ia bisa dipidanakan. Sepertinya sanksi kedualah yang akan ia
terima. Sebabnya, ia selalu berdalih.
Tak pernah mau mengakui kesalahannya. Kalau saja mengakui, bukan tak
mungkin nilai skripsinya hanya di-C-kan. C minus; itu di atas D, dan nilai
memalukan. Walau memalukan, setidaknya masih lumayan daripada dibatalkan atau
dipidanakan.
Sulis. Itulah nama mahasiswa kasus
plagiasi ini. Lima
huruf dan akhiran berbunyi mirip dengan… Entis. Cara ia menatap pun sama. Nanar
– seolah-olah ia polos. Naif – padahal bukti kejahatan sudah mengarah padanya.
Apakah Sulis merupakan reinkarnasi Entis? Entahlah. Lagipula di dalam agamaku
tak mengenal istilah ‘reinkarnasi’. Namun mengapakah bayangan Entis bisa tampak
dalam paras Sulis?
Sulis. Kasihan nian dirimu, nak.
Kau tak bisa mengelak lagi. Kau bahkan lupa menghapus jejak-jejak plagiasimu di
komputer jinjingmu sendiri. Alih-alih ingin membuktikan dirimu tak bersalah,
sang komputer malah mengkhianati tuannya sendiri. Miris nian. Kejahatanmu
memang tak tercium orang-orang terdekat; tapi barang matilah yang membuka kedok
polosmu itu.
Entis. Sulis. Kejahatan akan tetap
kalah oleh kebaikan. Tak ada gunanya memasang tampang naïf atau beraksi polos.
Sesungguhnya Tuhan maha tahu. Ia sendiri yang akan membuka tirai-tirai yang
menyelubungi kejahatan. Itu terbukti pada Entis dan Sulis.
Naif. Terkadang aku bertanya-tanya.
Masih adakah orang naïf di dunia ini? Kasus Entis dan Sulis membuatku sangsi
masih ada orang naïf di dunia. Sebab bagiku, naïf hanyalah sebuah kamuflase
untuk menutupi sesuatu yang tak ingin dipertunjukan.




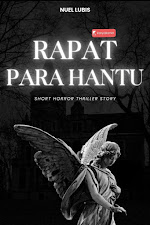

Keren euy tulisannya. Salut. :))
ReplyDeletebau bangkai tidak bisa di sembunyikan ya :)
ReplyDeleteDalem beneerrr!
ReplyDeleteGue udah baca duluan doong dari AOmagz! hehe
Http://AOmagz.blogspot.com
#SekalianPromo
#hehehe