"Kenapa aku WNI, Tuhan?"
Begitulah narasiku saat melihat serentetan berita seputar negara Jamrud Khatulistiwa ini. Mulai dari operasi tangkap tangan KPK yang melibatkan Wamenaker, joget-jogetnya Eko dan teman-teman Legislatif di Senayan, pernyataan blunder Nafa Urbach, hingga demonstrasi beberapa hari yang lalu di Senayan sana. Perihal gaji yang diterima anggota DPR dalam setahun.
Aku menatap layar ponsel dengan campuran getir dan pasrah. Notifikasi berita beruntun muncul, bak sirine darurat yang tak pernah padam. Satu berita belum kering dibaca, sudah disusul breaking news lain yang membuat keningku berkerut. Kadang aku berpikir, apakah berita di negeri ini memang sengaja dibuat seperti sinetron stripping? Episode demi episode, penuh drama, penuh plot twist, dan jarang ada ending yang memuaskan.
Rasanya, menjadi WNI itu campur aduk. Antara marah, bangga, lelah, cinta, kecewa.
Kadang aku iri dengan negara tetangga. Singapura misalnya, kecil tapi maju. Malaysia, meski juga punya kisruh politik, setidaknya masih lebih teratur. Sementara kita, dengan segala potensi yang luar biasa, seolah hanya bisa berputar-putar di lingkaran masalah yang sama: korupsi, oligarki, birokrasi.
Sungguh ironis!
Sekonyong-konyong aku ingat, beberapa tahun lalu pernah ada gurau di internet:
"Indonesia itu negeri kaya raya, tapi saking kayanya, semua orang di dalamnya ikut-ikutan kaya sendiri-sendiri."
Kalimat itu menohok. Kaya sumber daya, tapi miskin pengelolaan. Kaya slogan, miskin aksi nyata. Kaya drama, miskin solusi sayangnya.
Sementara aku, rakyat biasa, hanya bisa mengeluh lewat status media sosial atau tulisan kecil seperti ini.
Di layar ponsel, berita malam kembali menayangkan potongan sidang DPR. Kali ini tentang naiknya penghasilan para wakil rakyat. Entah mengapa malah terasa makin menjauhkan rakyat dari keadilan. Aku menonton dengan separuh hati.
Ada rasa jenuh. Rasa ingin menutup mata dan pura-pura tidak tahu. Namun aku sadar, apatis bukan jalan keluar. Kalau semua orang memilih diam, negeri ini akan terus dikuasai mereka yang tak peduli pada rakyat.
Tiba-tiba aku teringat kalimat Pramoedya Ananta Toer.
"Kalau orang miskin tidak boleh bermimpi, orang kaya akan berkuasa selamanya."
Mungkin tugas kita sebagai WNI bukan hanya menerima, tapi juga terus bermimpi, terus bersuara, meski suara itu kecil. Karena siapa tahu, dari suara-suara kecil itu, lahirlah perubahan besar.
Semasa kuliah dulu, kawan-kawanku di tongkrongan sering menjadikan politik sebagai bahan guyonan.
"Lihat tuh, anggota DPR joget-joget waktu sidang. Kalau kayak gini mah, lebih pantas masuk audisi Dangdut Academy daripada duduk di kursi parlemen," kata Wahyudi sambil menyeruput es teh. Kami semua tertawa, tapi tawa itu pahit.
"Yaelah, jangan salah. Mereka itu nggak main-main. Sekali setahun gaji mereka bisa buat kita kuliah sampai S3," timpal Erwin.
Aku hanya menghela napas. Kadang memang hanya bisa pasrah. Mau bicara panjang lebar, percuma. Kami hanya rakyat jelata, pekerja dengan gaji pas-pasan yang pajaknya justru ikut menyumbang kesejahteraan mereka.
Kamis, 21 Agustus 2025
Di balik pasrah itu, ada perasaan getir. Aku bertanya-tanya, apakah memang seperti ini takdir bangsa? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar sedang dimainkan di balik layar, yang kami tak bisa pahami?
Scrolling lagi, aku menemukan video seorang mahasiswa yang berorasi di tengah demo di Senayan. Suaranya lantang, penuh semangat:
"Ini bukan sekadar soal angka gaji, kawan-kawan! Ini soal jarak yang semakin lebar antara rakyat dengan wakil rakyatnya! Soal ketidakadilan yang kita biarkan berlarut-larut!"
Aku merinding mendengarnya. Suara itu mengingatkanku pada buku sejarah SMA dulu, tentang reformasi, tentang mahasiswa tahun 1998 yang berani menantang rezim. Yang membedakan nya adalah, dulu lawannya itu diktator yang menguasai sekian tahun. Untuk sekarang, lawannya adalah sistem yang sama-sama penuh jebakan, tapi lebih licin, lihai, dan cukup sulit dijatuhkan.
Aku sontak bertanya-tanya, apakah mahasiswa hari ini punya daya yang sama seperti kakak-kakak mereka dulu? Ataukah suara mereka hanya akan hilang ditelan algoritma media sosial, terganti dengan trending baru besok pagi?
"Kenapa aku WNI, Tuhan?"
Pertanyaan itu bukan berarti aku membenci tanah airku. Justru sebaliknya. Aku terlalu cinta, hingga sakit hati melihatnya begini. Aku ingin negeri ini berbenah, tapi tiap kali berharap, yang datang justru berita buruk.
Jumat, 22 Agustus 2025
Mendadak aku teringat 11-12 tahun yang lalu. Saat aku duduk di depan gerbang kampus. Di samping, ada kawanku sedang asyik merokok. Rokoknya kretek. Asalnya diembus ke langit lepas.
"Bro, kalau ada kesempatan, lo pindah negara nggak?" tanya Ermen tiba-tiba.
Pertanyaan itu membuat suasana hening sejenak.
Aku mengaduk kopi yang tadi aku beli dari Tukang Starling. Lama aku termenung sebelum akhirnya menjawab, "Pindah? Kadang pengen, Men. Tapi apa iya semudah itu? Kita emang bisa kabur dari paspor, tapi bisa nggak kabur dari identitas? Ini soal identitas diri!"
"Lo terlalu filosofis, bro," Ermen terkekeh. "Jadi keinget kelas Kewarganegaraan-nya Stephanus Desi.
Aku menatapnya serius. "Gue WNI. Mau keluar negeri sejauh apa pun, tetap aja di paspor tertulis: Indonesia. Kita ini nggak bisa lari dari kenyataan."
"Jadi?" Ermen menyela.
Aku tersenyum getir. "Jadi ya... meski gue kadang kecewa, marah, pengen protes, pada akhirnya gue tetap balik lagi ke pertanyaan tadi. Kenapa aku WNI, Tuhan? Mungkin karena Tuhan tahu, meski gue suka ngeluh, kenyataannya gue nggak bisa benar-benar benci negeri ini."
Sabtu, 23 Agustus 2025
Minggu, 24 Agustus 2025
Senin, 25 Agustus 2025
Selasa, 26 Agustus 2025
Rabu, 27 Agustus 2025
Kamis, 28 Agustus 2025
"Kenapa aku WNI, Tuhan?"
Mungkin jawabannya sederhana. Karena di negeri inilah aku lahir, tumbuh, jatuh cinta, tertawa, menangis. Karena di tanah inilah ada aroma nasi uduk pagi hari, suara azan bercampur lonceng gereja, tawa anak-anak main layangan, dan wajah orang-orang yang kucinta.
Mungkin karena negeri ini, seburuk apa pun beritanya, tetap punya ruang harapan. Harapan yang membuatku, meski kecewa berkali-kali, masih betah menulis, masih betah mengeluh, masih betah bermimpi.
Mungkin, hanya mungkin, Tuhan ingin aku tidak sekadar bertanya kenapa aku WNI, tapi juga berani menjawab:
"Karena aku yang harus ikut merawat negeri ini. Dengan caraku, sekecil apa pun."
Malam semakin larut. Kopi di gelas sudah dingin. Berita di televisi masih sama. Tak habis-habis membahas tentang DPR dan demonstrasi tersebut. Namun di hatiku ada secuil ketenangan.
Aku menghela napas panjang, lalu tersenyum getir.
"Ya sudah, Tuhan. Kalau memang ini jalan hidupku, jadikan aku WNI yang nggak cuma bisa mengeluh. Jadikan aku WNI yang masih mau peduli."
Aku tahu, di luar sana, ada banyak orang yang mungkin berpikir hal sama.













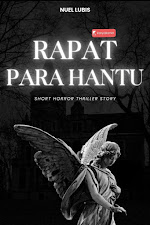

Comments
Post a Comment
Pembaca yang baik adalah yang sudi mau meninggalkan komentar. ^_^
Nice reader is the one who will leave lot of words in the comment box. ^_^